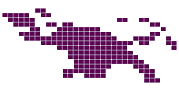Manula Mendaki Cartenz, Gunung Tertinggi Indonesia
pada tanggal
Selasa, 13 Agustus 2013
JAKARTA - Beda usia di antara kami 42 tahun. Termuda, Ridwan Hakim, baru 21 tahun, masih mahasiswa jurusan Kimia di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Tertua, Agam Napitupulu, pensiunan bankir, baru 63 tahun. Pemimpin pendakian, Fandhi Ahmad yang biasa dipanggil Agi, sudah 30 tahun. Saya, masih 54 tahun, sebelumnya sudah tiga kali mendaki Carstensz Pyramid (4.884 mdpl). Kami semua anggota Mapala Universitas Indonesia (Mapala UI).
Ide pendakian ini datang dari Agam Napitupulu. Ia bercita-cita mendaki seluruh tujuh gunung tertinggi di tujuh pulau, kepulauan besar Nusantara. Kerinci (3.805 mdpl) di Sumatera, Semeru (3.676 mdpl) di Jawa, Rinjani (3.726 mdpl) di Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara dan Bali), Bukit Raya (2.278 mdpl) di Kalimantan, Rantemario (3.478 mdpl) di Sulawesi, Binaiya (3.027 mdpl) di Kepulauan Maluku, dan Carstensz Pyramid di Papua. Tiga bulan sebelum keberangkatan kami pada 7 Juli 2013, Agam mengabarkan dia mendaki Bukit Raya gunung keenamnya, tinggal Carstensz Pyramid.
Agam pun mengajak Agi, yang sudah lima kali mengantarkan kru televisi, ibu-ibu pendaki, dan lainnya ke Carstensz. Agi memilih lewat jalur Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Jalur ini kini kerap digunakan para pendaki asing untuk mencapai kemah induk Lembah Danau-danau (4.200 mdpl).
Jalur Sugapa tidak mudah karena mencapai ke Lembah Danau-danau membutuhkan enam hari perjalanan. Agi pun meminta Ridwan ikut. Ridwan, teman mendakinya di jalur baru Puncak Trikora yang mereka capai pada awal tahun ini. Entah kenapa, Agam meminta saya ikut. Padahal saya terakhir kali mendaki satu setengah tahun lalu. Awal 2012, tepatnya bulan Februari, saya mendaki Gunung Salak, mengantar kenalan yang ingin mendoakan istrinya, pramugari korban musibah penerbangan di gunung setinggi 2.211 mdpl. Kami kemalaman dan ketika turun saya jatuh terperosok jalur air. Kaki saya cedera hingga enam bulan tidak bisa rutin olahraga jogging.
Agam bukan bankir sukses jika tidak bisa menjual idenya ke saya. Buktinya, saya pun ikut serta walau 20 tahun lalu setelah melewati jalur Sugapa saya berjanji dalam hati tidak akan lewat jalur itu lagi. Pasalnya, saya harus meniti setapak di sisi air terjun, dan berjam-jam menelusuri sungai kecil yang licin penuh batu berlumut.
20 Tahun Kemudian
Kami berada di Nabire (Rabu, 09/07/2013) menimbang badan untuk bisa beli tiket Aviastar. Penerbangan regular di pedalaman, sudah setara dengan tren terbaru di Eropa. Harga tiket mengikuti berat badan. Tidak dinyana, harga penerbangan 45 menit dari Nabire ke Bilogay sama dengan biaya penerbangan Jakarta-Nabire.
Di gudang bandara kami melihat tumpukan pagar besi, kantung-kantung semen, telur, sayur. Ketika bertanya pada petugas Aviastar, ternyata itu untuk diangkut ke Bilogay. Bilogay, desa kecil berbandara perintis adalah bagian dari “kota” Sugapa. Sejak 2008, Sugapa menjadi ibu kota Kabupaten Intan Jaya, pemekaran dari kabupaten Paniai dengan ibu kota Nabire. Namun beda dengan Nabire yang bisa menyediakan segala kebutuhannya melalui pelabuhan laut, Sugapa harus mendapatkan pagar besi untuk rumah pejabat atau kantor dinasnya dengan pesawat kecil berpenumpang hanya tiga sampai 14 orang saja, Pilatus Porter atau Twin Otter.
Ketika pesawat Twin Otter Aviastar menjelang Bilogay, saya terkejut melihat landasan sudah hitam legam, diaspal. Tarmac yang puluhan tahun lalu saya lalui, masih lapangan rumput sempit. Atap seng sudah memenuhi sekeliling bandara perintis ini. Warung-warung berteralis kawat berderet-deret di tepi bandara. Di Bilogay masih seperti dulu, tidak ada bangunan di tepi landasan. Barang ditumpuk saja di tepi dan penumpang berhamburan keluar menjauh dari propeler pesawat mencari ojek.
Ini semua hasil positif pemekaran daerah. Dua puluh tahun lalu saya hanya menginap di rumah kayu jauh dari tetangga, di bawah bandara. Jika mendengar suara pesawat datang, saya harus berlari-lari mendaki. Malam gelap gulita tidak ada lampu listrik. Saat itu Sugapa masih kecamatan.
Perubahan paling mencolok adalah ojek. Megapro, Byson, bahkan yang terbaru Versa 150cc sudah berbaris rapi. Tidak aneh pemandangan pengemudi ojek bersepatu boots karet, helm full face, dengan penumpang yang telanjang dada hanya mengenakan koteka saja. Ojek ini pun yang membawa kami ke dusun terakhir Zanamba di desa Swanggama. Dari Swanggama ini kami memulai pendakian menyusuri ke hulu daerah aliran sungai (DAS) Kemabu.
Plato Zenggilorong
Sungai utama Kemabu masih kami ikuti ke arah timur sampai Zanamba. Dari Zanamba kami mengikut anak sungai Yabu, melalui tambang garam dan bermalam di tepinya. Ternyata kekhawatiran saya bahwa jalur Sugapa ini berbahaya dan melelahkan tidak salah. Jalan ke tambang garam melalui longsoran dengan jurang sungai deras di bawahnya. Agam, membahas sungai itu dari sudut pandang arung jeram. Kelasnya sudah di atas 5 alias unrunable. “Kalau jatuh baru keluar di Memberamo,” simpul Agam.
Hari kedua, kami mencapai sungai kecil di dataran tinggi. Ketinggian sudah 3.500 mdpl. Sungai disebut oleh porter kami sebagai Ebay, dan perkemahan kami Endatapa. Esoknya kami bermalam di perkemahan yang mereka sebut Ebay. Perkemahan berada di atas lereng punggungan yang membatasi lereng lembah DAS Yabu dengan dataran tinggi Plato Zenggilorong. Di Zenggilorong memang terdapat banyak sungai kecil. Salah satunya kami seberangi saat mencapai dasar punggungan dan memasuki dataran tinggi. Saya duga itu hulu Sungai Ebay yang dua hari lalu kami berkemah di tepiannya di Endatapa.
Pada tengah hari keempat, kami menyeberangi hulu Sungai Kemabu. Saya kenali sungai ini dari perjalanan 20 tahun lalu ketika menyeberang Plato Zenggilorong dari Ilaga. Kami bermalam di Nasidomeh, perkemahan yang bersejarah. Nasidomeh dalam bahasa Dani artinya “rumah nasi (yang berlimpah)”. Di lokasi itu rombongan pendaki, Philip Temple yang menemukan jalur celah New Zealand mendapatkan drop bahan makanan dari udara. Ketika para porter suku Dani dari Ilaga yang mengiringinya mendapatkan ini pada 1961, mereka pun menyebut tempat mereka bermalam sebagai rumah nasi. Di tempat ini pula kisah para pendaki Mapala UI tahun ‘70-an, Herman Lantang, Heru Budiargo, Edi Wuryantoro, almarhum Hendry Walandouw dan lainnya pernah bermalam. Cerita-cerita legenda bagi kami, anggota Mapala UI.
Jejak Seven Summits
Hampir 30 tahun lalu, saya mengantarkan Pat dan Baiba Morrow serta Steve Fosset. Pada 1986, mereka menjadi pendaki asing pertama yang mendapat izin resmi Indonesia ke Carstensz. Pat sudah lebih setahun mengusahakan izin, ia melibatkan Mapala UI sebagai liason. Saya dan Titus Pramono diminta menemani karena kami beberapa bulan sebelumnya baru kembali dari Carstensz.
Pat berhasil dan kiprahnya itu menjadikan Carstensz Pyramid bagian dari Seven Summits, puncak tertinggi di ketujuh benua bumi. Carstensz tertinggi di antara Himalaya dan Andes ini mewakil benua Australasia. Sejak itu, Carstensz Pyramid ditawarkan secara komersial pada para peminat Seven Summits dengan banderol US$ 18.000 ex Timika, Papua.
Rabu (17/07/2013), kembali saya mengikuti jejak 30 tahun lalu. Mengantar seorang teman menuju puncak tertinggi di sisi barat Samudra Pasifik. Bagi pendaki Seven Summits, Carstensz unik. Satunya-satunya gunung batu yang membutuhkan teknik panjat tebing untuk mencapai puncaknya. Bahkan beberapa pendaki yang tidak akrab memanjat, menilai Carstensz lebih sulit dari Everest. Pat pun dalam buku seven summits-nya, Beyond Everest, memberikan tingkat kesulitan tinggi bagi Carstensz.
Bagi Agam, jalan pulang balik di jalur Sugapa juga bukan sembarangan. Kaki terjerembab dalam lumpur sedalam dengkul sangat melelahkan. Ia mendaki Carstensz dengan berjam-jam meniti tali menggunakan ascender yang juga melelahkan. Maklum ia juga baru kenal teknik panjat tebing hanya beberapa jam saja, latihan mingguan di dinding panjat buatan di kampus Universitas Indonesia.
Di punggung puncak itu, kami diberkahi ketika awan tersibak. Di bawah, ke arah timur, kami melihat aktivitas tambang PT Freeport Indonesia. Sungguh berbeda dengan 30 tahun lalu. Tidak tampak aktivitas tambang kala itu, Grassberg masih seperti namanya bukit rerumputan. Sekarang Carstensz tidak lagi terasa terpencil dan sepi. Bagi saya, sangat mengganggu melihat musnahnya keheningan alam.
Kami tiba di puncak Carstensz Pyramid pada pukul 14.00 WIT lewat sedikit, setelah berangkat sejak pukul 03.00 pagi di Lembah Danau-danau. Tentu saja tiba di puncak seperti baru selesai lari maraton saja. Sebentar foto-foto, makan buah kaleng yang menjadi tradisi Agam Napitupulu saat mencapai puncak. Dan kami pun bersiap-siap turun, meniti tali ratusan meter untuk kembali ke kemah induk, delapan jam kemudian. [SinarHarapan]
Ide pendakian ini datang dari Agam Napitupulu. Ia bercita-cita mendaki seluruh tujuh gunung tertinggi di tujuh pulau, kepulauan besar Nusantara. Kerinci (3.805 mdpl) di Sumatera, Semeru (3.676 mdpl) di Jawa, Rinjani (3.726 mdpl) di Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara dan Bali), Bukit Raya (2.278 mdpl) di Kalimantan, Rantemario (3.478 mdpl) di Sulawesi, Binaiya (3.027 mdpl) di Kepulauan Maluku, dan Carstensz Pyramid di Papua. Tiga bulan sebelum keberangkatan kami pada 7 Juli 2013, Agam mengabarkan dia mendaki Bukit Raya gunung keenamnya, tinggal Carstensz Pyramid.
Agam pun mengajak Agi, yang sudah lima kali mengantarkan kru televisi, ibu-ibu pendaki, dan lainnya ke Carstensz. Agi memilih lewat jalur Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Jalur ini kini kerap digunakan para pendaki asing untuk mencapai kemah induk Lembah Danau-danau (4.200 mdpl).
Jalur Sugapa tidak mudah karena mencapai ke Lembah Danau-danau membutuhkan enam hari perjalanan. Agi pun meminta Ridwan ikut. Ridwan, teman mendakinya di jalur baru Puncak Trikora yang mereka capai pada awal tahun ini. Entah kenapa, Agam meminta saya ikut. Padahal saya terakhir kali mendaki satu setengah tahun lalu. Awal 2012, tepatnya bulan Februari, saya mendaki Gunung Salak, mengantar kenalan yang ingin mendoakan istrinya, pramugari korban musibah penerbangan di gunung setinggi 2.211 mdpl. Kami kemalaman dan ketika turun saya jatuh terperosok jalur air. Kaki saya cedera hingga enam bulan tidak bisa rutin olahraga jogging.
Agam bukan bankir sukses jika tidak bisa menjual idenya ke saya. Buktinya, saya pun ikut serta walau 20 tahun lalu setelah melewati jalur Sugapa saya berjanji dalam hati tidak akan lewat jalur itu lagi. Pasalnya, saya harus meniti setapak di sisi air terjun, dan berjam-jam menelusuri sungai kecil yang licin penuh batu berlumut.
20 Tahun Kemudian
Kami berada di Nabire (Rabu, 09/07/2013) menimbang badan untuk bisa beli tiket Aviastar. Penerbangan regular di pedalaman, sudah setara dengan tren terbaru di Eropa. Harga tiket mengikuti berat badan. Tidak dinyana, harga penerbangan 45 menit dari Nabire ke Bilogay sama dengan biaya penerbangan Jakarta-Nabire.
Di gudang bandara kami melihat tumpukan pagar besi, kantung-kantung semen, telur, sayur. Ketika bertanya pada petugas Aviastar, ternyata itu untuk diangkut ke Bilogay. Bilogay, desa kecil berbandara perintis adalah bagian dari “kota” Sugapa. Sejak 2008, Sugapa menjadi ibu kota Kabupaten Intan Jaya, pemekaran dari kabupaten Paniai dengan ibu kota Nabire. Namun beda dengan Nabire yang bisa menyediakan segala kebutuhannya melalui pelabuhan laut, Sugapa harus mendapatkan pagar besi untuk rumah pejabat atau kantor dinasnya dengan pesawat kecil berpenumpang hanya tiga sampai 14 orang saja, Pilatus Porter atau Twin Otter.
Ketika pesawat Twin Otter Aviastar menjelang Bilogay, saya terkejut melihat landasan sudah hitam legam, diaspal. Tarmac yang puluhan tahun lalu saya lalui, masih lapangan rumput sempit. Atap seng sudah memenuhi sekeliling bandara perintis ini. Warung-warung berteralis kawat berderet-deret di tepi bandara. Di Bilogay masih seperti dulu, tidak ada bangunan di tepi landasan. Barang ditumpuk saja di tepi dan penumpang berhamburan keluar menjauh dari propeler pesawat mencari ojek.
Ini semua hasil positif pemekaran daerah. Dua puluh tahun lalu saya hanya menginap di rumah kayu jauh dari tetangga, di bawah bandara. Jika mendengar suara pesawat datang, saya harus berlari-lari mendaki. Malam gelap gulita tidak ada lampu listrik. Saat itu Sugapa masih kecamatan.
Perubahan paling mencolok adalah ojek. Megapro, Byson, bahkan yang terbaru Versa 150cc sudah berbaris rapi. Tidak aneh pemandangan pengemudi ojek bersepatu boots karet, helm full face, dengan penumpang yang telanjang dada hanya mengenakan koteka saja. Ojek ini pun yang membawa kami ke dusun terakhir Zanamba di desa Swanggama. Dari Swanggama ini kami memulai pendakian menyusuri ke hulu daerah aliran sungai (DAS) Kemabu.
Plato Zenggilorong
Sungai utama Kemabu masih kami ikuti ke arah timur sampai Zanamba. Dari Zanamba kami mengikut anak sungai Yabu, melalui tambang garam dan bermalam di tepinya. Ternyata kekhawatiran saya bahwa jalur Sugapa ini berbahaya dan melelahkan tidak salah. Jalan ke tambang garam melalui longsoran dengan jurang sungai deras di bawahnya. Agam, membahas sungai itu dari sudut pandang arung jeram. Kelasnya sudah di atas 5 alias unrunable. “Kalau jatuh baru keluar di Memberamo,” simpul Agam.
Hari kedua, kami mencapai sungai kecil di dataran tinggi. Ketinggian sudah 3.500 mdpl. Sungai disebut oleh porter kami sebagai Ebay, dan perkemahan kami Endatapa. Esoknya kami bermalam di perkemahan yang mereka sebut Ebay. Perkemahan berada di atas lereng punggungan yang membatasi lereng lembah DAS Yabu dengan dataran tinggi Plato Zenggilorong. Di Zenggilorong memang terdapat banyak sungai kecil. Salah satunya kami seberangi saat mencapai dasar punggungan dan memasuki dataran tinggi. Saya duga itu hulu Sungai Ebay yang dua hari lalu kami berkemah di tepiannya di Endatapa.
Pada tengah hari keempat, kami menyeberangi hulu Sungai Kemabu. Saya kenali sungai ini dari perjalanan 20 tahun lalu ketika menyeberang Plato Zenggilorong dari Ilaga. Kami bermalam di Nasidomeh, perkemahan yang bersejarah. Nasidomeh dalam bahasa Dani artinya “rumah nasi (yang berlimpah)”. Di lokasi itu rombongan pendaki, Philip Temple yang menemukan jalur celah New Zealand mendapatkan drop bahan makanan dari udara. Ketika para porter suku Dani dari Ilaga yang mengiringinya mendapatkan ini pada 1961, mereka pun menyebut tempat mereka bermalam sebagai rumah nasi. Di tempat ini pula kisah para pendaki Mapala UI tahun ‘70-an, Herman Lantang, Heru Budiargo, Edi Wuryantoro, almarhum Hendry Walandouw dan lainnya pernah bermalam. Cerita-cerita legenda bagi kami, anggota Mapala UI.
Jejak Seven Summits
Hampir 30 tahun lalu, saya mengantarkan Pat dan Baiba Morrow serta Steve Fosset. Pada 1986, mereka menjadi pendaki asing pertama yang mendapat izin resmi Indonesia ke Carstensz. Pat sudah lebih setahun mengusahakan izin, ia melibatkan Mapala UI sebagai liason. Saya dan Titus Pramono diminta menemani karena kami beberapa bulan sebelumnya baru kembali dari Carstensz.
Pat berhasil dan kiprahnya itu menjadikan Carstensz Pyramid bagian dari Seven Summits, puncak tertinggi di ketujuh benua bumi. Carstensz tertinggi di antara Himalaya dan Andes ini mewakil benua Australasia. Sejak itu, Carstensz Pyramid ditawarkan secara komersial pada para peminat Seven Summits dengan banderol US$ 18.000 ex Timika, Papua.
Rabu (17/07/2013), kembali saya mengikuti jejak 30 tahun lalu. Mengantar seorang teman menuju puncak tertinggi di sisi barat Samudra Pasifik. Bagi pendaki Seven Summits, Carstensz unik. Satunya-satunya gunung batu yang membutuhkan teknik panjat tebing untuk mencapai puncaknya. Bahkan beberapa pendaki yang tidak akrab memanjat, menilai Carstensz lebih sulit dari Everest. Pat pun dalam buku seven summits-nya, Beyond Everest, memberikan tingkat kesulitan tinggi bagi Carstensz.
Bagi Agam, jalan pulang balik di jalur Sugapa juga bukan sembarangan. Kaki terjerembab dalam lumpur sedalam dengkul sangat melelahkan. Ia mendaki Carstensz dengan berjam-jam meniti tali menggunakan ascender yang juga melelahkan. Maklum ia juga baru kenal teknik panjat tebing hanya beberapa jam saja, latihan mingguan di dinding panjat buatan di kampus Universitas Indonesia.
Di punggung puncak itu, kami diberkahi ketika awan tersibak. Di bawah, ke arah timur, kami melihat aktivitas tambang PT Freeport Indonesia. Sungguh berbeda dengan 30 tahun lalu. Tidak tampak aktivitas tambang kala itu, Grassberg masih seperti namanya bukit rerumputan. Sekarang Carstensz tidak lagi terasa terpencil dan sepi. Bagi saya, sangat mengganggu melihat musnahnya keheningan alam.
Kami tiba di puncak Carstensz Pyramid pada pukul 14.00 WIT lewat sedikit, setelah berangkat sejak pukul 03.00 pagi di Lembah Danau-danau. Tentu saja tiba di puncak seperti baru selesai lari maraton saja. Sebentar foto-foto, makan buah kaleng yang menjadi tradisi Agam Napitupulu saat mencapai puncak. Dan kami pun bersiap-siap turun, meniti tali ratusan meter untuk kembali ke kemah induk, delapan jam kemudian. [SinarHarapan]